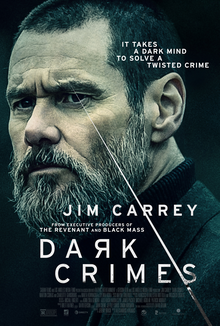Judul : Review Film: 'Us' (2019)
link : Review Film: 'Us' (2019)
Thriller
'Us' adalah salah satu film paling mendebarkan dalam beberapa tahun belakangan.

“... looks like one f***up performance art.”Rating UP:
— Gabe Wilson
Mungkin baru sekitar setengah film Us berjalan, teman nonton saya tiba-tiba komplain:
"
Saya —sebagai seorang blogger film, seorang penikmat film, dan seseorang yang mengaku-ngaku paham banget soal film padahal bukan— tidak terkejut, apalagi marah. Sebab, saya juga capek. Lha gimana, jantung saya yang sudah tua ini digedor terus, hampir secara konstan sepanjang film. Us adalah salah satu film paling mendebarkan dalam beberapa tahun belakangan. Saya pernah melihat film yang adegannya lebih sadis. Saya pernah melihat film yang jump-scares-nya lebih berisik. Namun, Us lebih berhak mendapat predikat horor sejati di antara semuanya. Jarang-jarang saya nonton setegang ini.
Dua tahun lalu, Jordan Peele memulai debutnya sebagai penulis dan sutradara dengan menghadirkan salah satu horor/thriller paling orisinal, Get Out. Film tersebut sangat tajam dalam menyampaikan pesan sosiopolitisnya, tapi buat saya tak begitu menakutkan. Sekarang ia membawakan Us, film yang tak begitu orisinal tapi anjir sangat menakutkan. Film ini menempeleng saya yang awalnya masih meragukan soal kapabilitasnya sebagai sutradara hqq di Get Out, karena sekarang ia membuktikan bahwa ia bisa membuat film horor yang benar-benar horor jika dibutuhkan.
Peele menangani premis klise home-invasion dari filmnya menjadi horor yang cerdas dan terasa segar. Sebagaimana yang kita harapkan dari seorang motor penggerak sketsa legendaris Key & Peele-nya Comedy Central, ia kembali dengan piawai menggabungkan horor dengan komedi, bukan lewat adegan "eh, gue pengen ngelucu nih" melainkan lewat kecanggungan situasi. Ini menjamin bahwa kita ketawa bukan berarti lepas dari cengkeraman film. Namun yang lebih saya kagumi adalah bagaimana ia dengan brilian menciptakan kengerian yang sangat nampol lewat sesuatu yang relatif sederhana. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh kita. Us.
Lebih tepatnya, terornya dibawa oleh sesuatu yang terlihat persis seperti kita. Atau, apa memang begitu? Seorang gadis kecil (Madison Curry) menemukan hal ini saat nyasar di sebuah taman bermain di pantai Santa Cruz. Peristiwa ini meninggalkan trauma sedemikian mendalam sehingga membuat sang gadis kecil yang tumbuh menjadi Lupita Nyong'o, gampang resah serta overprotektif terhadap kedua anaknya (Shahadi Wright Joseph dan Evan Alex). Sialnya, sang suami yang selow abis (Winston Duke) membawanya sekeluarga untuk liburan di wisma yang dekat dengan pantai naas tersebut.
Sungguh awal cerita yang klise. Tapi saya tidak mendelik. Pasalnya, Peele menuturkan ini dengan sangat cakap. Ia membangun karakter dan situasi dengan perlahan tapi mantap. Saya kira poin krusial dari film ini adalah membawa kita masuk ke dalam kondisi pikiran karakter Nyong'o. Dan Peele berhasil melakukannya. Ia sepertinya sangat menguasai komando di setiap lini. Ketegangan tercipta secara simultan lewat akting, pemilihan gambar, dan scoring, dengan kontibusi besar dari semua aktor, sinematografer Mike Gioulakis dan komposer Michael Abels. Baru beberapa menit berjalan, film sudah mencengkeram saya.
Dikarenakan ini adalah spoiler, maka saya takkan memberitahu anda bahwa keluarga Nyong'o akan diinvasi oleh satu keluarga yang sangat mirip dengan mereka. Sial, saya keceplosan. Mereka berdiri di luar rumah dengan posisi kaku, memakai baju terusan warna merah dan bersenjatakan gunting besar berwarna emas. Maksud kedatangan mereka adalah berkunjung dan bercengkerama sambil ngopi santai... tentu saja bukan! Mereka tidak datang dalam damai.
Istilah yang kerap diasosiasikan dengan film Us —meski filmnya sendiri tak pernah menyebut kata ini— adalah Doppelganger. Doppelganger adalah orang yang sangat mirip dengan kita padahal kita tak punya hubungan sama sekali dengan mereka. Konon, bertemu dengan doppelganger adalah pertanda buruk yang bisa berujung pada kematian. Dan sebagaimana resep jitu yang sudah diterapkan oleh manusia sejak jaman dahulu kala; kalau ada sesuatu yang mirip dengan kita, bergerak seperti kita, berbicara seperti kita, bernapas seperti kita, tapi bukan bagian dari kita, maka layak, wajar, dan pantas kita serbu. Uhuk #PesanMoral.
Kembali ke topik, premis ini mengijinkan hampir semua aktornya punya peran ganda. Ternyata menakutkan juga melihat versi jahat dari kita menyerang diri kita sendiri. Semua mendapat momen masing-masing, termasuk Elisabeth Moss dan Tim Heidecker yang bermain sebagai pasangan yang merupakan teman keluarga Nyong'o. Namun yang paling spektakuler, tentunya Nyong'o. Penampilan dobelnya punya kualitas emosional dan fisik yang fantastis. Versi jahatnya barangkali merupakan satu-satunya doppelganger yang bisa bicara; itupun dalam suara yang serak ke dalam. Saat hubungan mereka terungkap lebih dalam, ini membeberkan sesuatu yang lebih mengerikan.
Skala ceritanya pun meluas, lebih dari sekadar home-invasion, karena ia kemudian melibatkan konsep scifi yang sangat ambisius. Dan dengan lebih banyak simbolisme dan subteks. Inilah saat kita teringat kembali dengan teks di awal film yang memberitahu soal banyaknya terowongan rahasia di bawah Amerika. Atau soal berita di televisi jadul yang mewartakan soal aksi "Hands Across America", kegiatan amal yang melibatkan 6 juta warga Amerika bergandeng tangan di seluruh negeri (entah jumlahnya betul atau tidak). Atau soal surat Jeremiah 11:11 tentang Tuhan yang memberi bencana. Atau soal puluhan kelinci dalam kandang yang menjadi adegan pengantar judul film. Semuanya seperti mengisyaratkan... uhm, sesuatu, tapi rasa-rasanya tak nyambung dalam satu konsep yang jelas. Us seperti ingin menyampaikan soal sesuatu, tapi tak tahu apa yang ingin disampaikannya.
Apakah ini soal dualitas dari kualitas pribadi manusia? Atau soal sindiran terhadap kemunafikan beberapa dari kita dalam setiap aksi amal? Atau soal pembalasan dari orang-orang yang direpresi di Amerika? Saya tak bisa menemukan tohokan utamanya. Mitologinya agak memusingkan kalau dipikirkan. Tapi, anda tahu? Saya tak begitu terpikir soal ini saat menonton. Setiap perkembangan cerita dalam Us membuat saya penasaran hanya untuk melihat kemana lagi Peele bisa membawa saya. Ia tak berhenti untuk menjanjikan sesuatu yang tak terduga. Dan ia tak pernah membuat saya kecewa. ■UP
Follow Ulasan Pilem di twitter: @ulasanpilem dan di instagram: @ulasanpilem
Kunjungi Ulasan Pilem di facebook: facebook.com/ulasanpilem


Us
116 menit
Remaja - BO
Jordan Peele
Jordan Peele
Jason Blum, Ian Cooper, Sean McKittrick, Jordan Peele
Mike Gioulakis
Michael Abels
Diulas oleh TEGUH RASPATI
'Us' adalah salah satu film paling mendebarkan dalam beberapa tahun belakangan.

“... looks like one f***up performance art.”Rating UP:
— Gabe Wilson
Mungkin baru sekitar setengah film Us berjalan, teman nonton saya tiba-tiba komplain:
"
Saya —sebagai seorang blogger film, seorang penikmat film, dan seseorang yang mengaku-ngaku paham banget soal film padahal bukan— tidak terkejut, apalagi marah. Sebab, saya juga capek. Lha gimana, jantung saya yang sudah tua ini digedor terus, hampir secara konstan sepanjang film. Us adalah salah satu film paling mendebarkan dalam beberapa tahun belakangan. Saya pernah melihat film yang adegannya lebih sadis. Saya pernah melihat film yang jump-scares-nya lebih berisik. Namun, Us lebih berhak mendapat predikat horor sejati di antara semuanya. Jarang-jarang saya nonton setegang ini.
Dua tahun lalu, Jordan Peele memulai debutnya sebagai penulis dan sutradara dengan menghadirkan salah satu horor/thriller paling orisinal, Get Out. Film tersebut sangat tajam dalam menyampaikan pesan sosiopolitisnya, tapi buat saya tak begitu menakutkan. Sekarang ia membawakan Us, film yang tak begitu orisinal tapi anjir sangat menakutkan. Film ini menempeleng saya yang awalnya masih meragukan soal kapabilitasnya sebagai sutradara hqq di Get Out, karena sekarang ia membuktikan bahwa ia bisa membuat film horor yang benar-benar horor jika dibutuhkan.
Peele menangani premis klise home-invasion dari filmnya menjadi horor yang cerdas dan terasa segar. Sebagaimana yang kita harapkan dari seorang motor penggerak sketsa legendaris Key & Peele-nya Comedy Central, ia kembali dengan piawai menggabungkan horor dengan komedi, bukan lewat adegan "eh, gue pengen ngelucu nih" melainkan lewat kecanggungan situasi. Ini menjamin bahwa kita ketawa bukan berarti lepas dari cengkeraman film. Namun yang lebih saya kagumi adalah bagaimana ia dengan brilian menciptakan kengerian yang sangat nampol lewat sesuatu yang relatif sederhana. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh kita. Us.
Lebih tepatnya, terornya dibawa oleh sesuatu yang terlihat persis seperti kita. Atau, apa memang begitu? Seorang gadis kecil (Madison Curry) menemukan hal ini saat nyasar di sebuah taman bermain di pantai Santa Cruz. Peristiwa ini meninggalkan trauma sedemikian mendalam sehingga membuat sang gadis kecil yang tumbuh menjadi Lupita Nyong'o, gampang resah serta overprotektif terhadap kedua anaknya (Shahadi Wright Joseph dan Evan Alex). Sialnya, sang suami yang selow abis (Winston Duke) membawanya sekeluarga untuk liburan di wisma yang dekat dengan pantai naas tersebut.
Sungguh awal cerita yang klise. Tapi saya tidak mendelik. Pasalnya, Peele menuturkan ini dengan sangat cakap. Ia membangun karakter dan situasi dengan perlahan tapi mantap. Saya kira poin krusial dari film ini adalah membawa kita masuk ke dalam kondisi pikiran karakter Nyong'o. Dan Peele berhasil melakukannya. Ia sepertinya sangat menguasai komando di setiap lini. Ketegangan tercipta secara simultan lewat akting, pemilihan gambar, dan scoring, dengan kontibusi besar dari semua aktor, sinematografer Mike Gioulakis dan komposer Michael Abels. Baru beberapa menit berjalan, film sudah mencengkeram saya.
Dikarenakan ini adalah spoiler, maka saya takkan memberitahu anda bahwa keluarga Nyong'o akan diinvasi oleh satu keluarga yang sangat mirip dengan mereka. Sial, saya keceplosan. Mereka berdiri di luar rumah dengan posisi kaku, memakai baju terusan warna merah dan bersenjatakan gunting besar berwarna emas. Maksud kedatangan mereka adalah berkunjung dan bercengkerama sambil ngopi santai... tentu saja bukan! Mereka tidak datang dalam damai.
Istilah yang kerap diasosiasikan dengan film Us —meski filmnya sendiri tak pernah menyebut kata ini— adalah Doppelganger. Doppelganger adalah orang yang sangat mirip dengan kita padahal kita tak punya hubungan sama sekali dengan mereka. Konon, bertemu dengan doppelganger adalah pertanda buruk yang bisa berujung pada kematian. Dan sebagaimana resep jitu yang sudah diterapkan oleh manusia sejak jaman dahulu kala; kalau ada sesuatu yang mirip dengan kita, bergerak seperti kita, berbicara seperti kita, bernapas seperti kita, tapi bukan bagian dari kita, maka layak, wajar, dan pantas kita serbu. Uhuk #PesanMoral.
Kembali ke topik, premis ini mengijinkan hampir semua aktornya punya peran ganda. Ternyata menakutkan juga melihat versi jahat dari kita menyerang diri kita sendiri. Semua mendapat momen masing-masing, termasuk Elisabeth Moss dan Tim Heidecker yang bermain sebagai pasangan yang merupakan teman keluarga Nyong'o. Namun yang paling spektakuler, tentunya Nyong'o. Penampilan dobelnya punya kualitas emosional dan fisik yang fantastis. Versi jahatnya barangkali merupakan satu-satunya doppelganger yang bisa bicara; itupun dalam suara yang serak ke dalam. Saat hubungan mereka terungkap lebih dalam, ini membeberkan sesuatu yang lebih mengerikan.
Skala ceritanya pun meluas, lebih dari sekadar home-invasion, karena ia kemudian melibatkan konsep scifi yang sangat ambisius. Dan dengan lebih banyak simbolisme dan subteks. Inilah saat kita teringat kembali dengan teks di awal film yang memberitahu soal banyaknya terowongan rahasia di bawah Amerika. Atau soal berita di televisi jadul yang mewartakan soal aksi "Hands Across America", kegiatan amal yang melibatkan 6 juta warga Amerika bergandeng tangan di seluruh negeri (entah jumlahnya betul atau tidak). Atau soal surat Jeremiah 11:11 tentang Tuhan yang memberi bencana. Atau soal puluhan kelinci dalam kandang yang menjadi adegan pengantar judul film. Semuanya seperti mengisyaratkan... uhm, sesuatu, tapi rasa-rasanya tak nyambung dalam satu konsep yang jelas. Us seperti ingin menyampaikan soal sesuatu, tapi tak tahu apa yang ingin disampaikannya.
Apakah ini soal dualitas dari kualitas pribadi manusia? Atau soal sindiran terhadap kemunafikan beberapa dari kita dalam setiap aksi amal? Atau soal pembalasan dari orang-orang yang direpresi di Amerika? Saya tak bisa menemukan tohokan utamanya. Mitologinya agak memusingkan kalau dipikirkan. Tapi, anda tahu? Saya tak begitu terpikir soal ini saat menonton. Setiap perkembangan cerita dalam Us membuat saya penasaran hanya untuk melihat kemana lagi Peele bisa membawa saya. Ia tak berhenti untuk menjanjikan sesuatu yang tak terduga. Dan ia tak pernah membuat saya kecewa. ■UP
Follow Ulasan Pilem di twitter: @ulasanpilem dan di instagram: @ulasanpilem
Kunjungi Ulasan Pilem di facebook: facebook.com/ulasanpilem