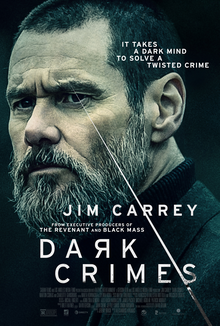Judul : Review Film: 'Burning' (2018)
link : Review Film: 'Burning' (2018)
Drama
'Burning' adalah pencapaian hebat dalam hal penciptaan suspens.

“Why do we live? What is the significance of living?”Rating UP:
— Shin Hae-mi
Sepanjang sejarah perfilman thriller, Burning barangkali merupakan salah satu film yang paling tak konklusif dari segi misteri. Namun, secara emosional, ia sangat memuaskan. Film ini dibangun dengan perlahan tapi sangat terukur, mencekat kita lewat cara yang tak terduga sembari memberi cukup ruang agar bobot emosionalnya terakumulasi dengan begitu hebat. Semua ini kemudian mengantarkan kita ke momen puncak yang saking gregetnya kita merasa sangat butuh sebuah pelepasan. Tidak bisa tidak. Wajib.
"Ya Tuhan, satu pelepasan saja dan saya akan lega," kita pikir.
Dan BAM! Burning memberikannya dengan cara dan waktu yang tepat.
Saya bisa menggambarkan Burning dengan deskripsi sederhana: sebuah cinta segitiga yang berujung pada cerita kriminal. Tapi saya bakal sotoy. Film ini jauh lebih kompleks daripada itu. Lagipula, saya tak tahu apakah deskripsi tersebut memang mewakili atau tidak. Saya bisa saja menonton film ini lebih dari 10 kali, dan ujung-ujungnya tetap saja tak bakal sepenuhnya yakin dengan apa yang (saya kira) saya lihat. Burning penuh dengan ketidakpastian dan justru itulah yang membuatnya sangat menegangkan.
Kita sebagai penonton, sama seperti para karakter di dalam film, tak persis tahu apa yang sebenarnya terjadi dan melihat karakter lain lewat kacamata masing-masing; persepsi yang sebetulnya hanyalah produk ambigu dari pengalaman hidup yang cuma sebentar dengan orang yang dimaksud. Apakah mereka memang betul seperti apa yang kita kira?
Mari kita mulai dengan karakter utama kita, Jongsu (Yoo Ah-in), pria kampung yang bercita-cita menjadi penulis walau saat ini hanya berkutat sebagai kurir di kota Seoul. Jongsu pendiam dan tak begitu ekspresif. Ia hanyalah pria biasa yang sama sekali tak mencolok. Namun seorang SPG seksi yang ditemuinya tak sengaja di jalan bilang bahwa mereka saling kenal. Katanya mereka dulu adalah teman sekelas di kampung. Jongsu melongo.
"Aku operasi plastik," celoteh si SPG. Cewek ini namanya Haemi (Jeon Jong-seo), seorang optimis, penuh semangat, dan tampaknya sangat polos. Saat nongkrong, Haemi kemudian bilang kepada Jongsu bahwa ia sedang mempelajari pantomim. Tak butuh lama, Jongsu diajak main ke apartemen Haemi dan mereka melakukan hal yang iya-iya disana.
Jelas sekali kalau Jongsu langsung merasa terikat dengan Haemi. Ia bahkan mau saja saat dimintai tolong untuk memberi makan kucing Haemi selama Haemi pergi ke Afrika dalam sebuah perjalanan mencari jati diri. Setiap hari Jongsu mengunjungi apartemen Haemi, dan setiap hari itu pula ia merancap sambil membayangkan Haemi.
Iya. Merancap. Jongsu memang punya kehidupan yang sedikit, ehm, ganjil. Ia seperti selalu sendirian dan tak punya satu pun teman. Kita mendengar bahwa ayahnya sedang dalam masalah, tapi kita tak perlu tahu persisnya apa. Kita tahu bahwa sang ibu sudah meninggalkannya. Kita tahu Jongsu rutin mengunjungi kebun ayahnya di kampung. Film menuturkan detail kehidupan Jongsu dengan perlahan dan telaten, tapi rasa-rasanya gambaran besarnya masih saja buram.
Namun yang lebih buram adalah Ben (Steven Yeun). Jongsu ketemu Ben saat menjemput Haemi di bandara sekembalinya dari Afrika. Situasi ini menciptakan hubungan segitiga yang tak nyaman. Ben adalah teman seperjalanan Haemi. Tapi mereka sepertinya sangat akrab. Apakah mereka jadian? Entahlah. Haemi sepertinya menikmati sekali saat jalan dengan Ben, tapi ia juga berusaha untuk selalu mengajak Jongsu. Ben tampaknya juga tak pernah keberatan.
Jongsu punya firasat buruk soal Ben. Ada sesuatu yang janggal dengan Ben; ia sosialita, punya mobil Porsche dan apartemen mewah, tapi kelihatannya tak punya pekerjaan. Kepribadiannya mulus tapi nyaris hampa, bahkan mungkin punya bakat psikopat. Ben memberitahu Jongsu dan Haemi bahwa ia tak pernah menangis seumur hidup. Penampilan Steven Yeun luar biasa; ia menciptakan karakter dingin yang penuh misteri.
Film ini memang punya kemasan thriller kriminal. Namun ia lebih terasa seperti studi psikologi karakter. Atau barangkali lebih tepat: permainan studi psikologi karakter. Kita melihat sesuatu cukup banyak, tapi kita tetap saja tak tahu banyak. Apa maksud Ben terhadap Jongsu? Atau terhadap Haemi?
Atau soal Haemi sendiri. Apakah ia benar bisa dipercaya? Apakah Jongsu dulu memang pernah menyelamatkan Haemi saat terjebak di sumur? Atau itu hanya karangan Haemi belaka? Cerita film ini seolah cerita antara dua orang pria yang sangat berbeda dengan satu wanita polos terjebak di tengahnya. Apa benar begitu? Kebenaran hakiki adalah sebuah kemustahilan dalam Burning. Kita diperdaya untuk membuat asumsi yang belum tentu kebenarannya.
Ketika Haemi tiba-tiba menghilang, Jongsu hampir sepenuhnya yakin bahwa pelakunya adalah Ben, walau tak ada bukti yang jelas. Ini memancing Jongsu untuk membuntuti Ben. Jongsu ingat bahwa Ben pernah bilang bahwa ia suka membakar greenhouse; bukan untuk apa-apa, melainkan hanya untuk sekadar melihat greenhouse tersebut terbakar. Dan target selanjutnya, kata Ben sembari tersenyum, berada sangat dekat dengan Jongsu. Jongsu sangat percaya dengan ini sampai ia mengecek semua greenhouse di kampungnya. Jongsu tak menemukan apapun. Apakah Ben benar-benar tukang bakar atau cuma sedang mempermainkannya?
Film ini digarap oleh sutradara Lee Chang-dong dari cerita pendek karya penulis kenamaan Jepang, Haruki Murakami. Plotnya terasa berjalan dengan alami meski latarnya diubah menjadi di Korea. Film Lee dengan luar biasa menangkap nuansa kesendirian dan hasrat terpendam yang kerap ditemui dalam karya Murakami. Poin utamanya adalah apa yang diutarakan Haemi kepada Jongsu sebelum berangkat ke Afrika: "Semua orang lapar akan sesuatu."
Burning adalah pencapaian hebat dalam hal penciptaan suspens. Kita sukses dijaga untuk merasa tak nyaman dalam durasinya yang sangat panjang, nyaris 3 jam. Metode narasinya barangkali adalah aplikasi sinematis dari teori Kucing Schrodinger. Teori ini menyebutkan bahwa seekor kucing yang dimasukkan ke dalam kotak radioaktif, berada dalam kondisi hidup dan mati secara simultan. Kita belum tahu status kucingnya almarhum atau bukan sebelum kita melihat isi kotak tersebut. Entah sengaja atau tidak, Lee bahkan menyelipkan Kucing Schrodinger ala-ala ke dalam Burning. Jongsu dengan rutin memberi makan kucing Haemi, tapi ia tak pernah melihat wujud kucing tersebut. Meski begitu, makanannya selalu habis.
Saya sengaja bawa-bawa teori fisika kuantum biar dibilang intelek.
Lee tidak menciptakan Kucing Schrodinger-nya dengan manipulasi palsu. Alih-alih, ia melakukannya dengan memberikan latar situasi yang sedemikian kompleks demi menciptakan tensi. Ada perbedaan strata sosial dan kepribadian yang mencolok antara Jongsu dengan Ben. Apakah Jongsu merasa iri terhadap Ben? Ataukah Jongsu murka karena Ben tak mengapresiasi Haemi seperti ia menyukai Haemi? Saat Haemi bercerita di depan teman-teman Ben, Jongsu melihat sekilas Ben yang menguap bosan. Dan barangkali tak tahu itu semua, Haemi malah dengan nyaman menari bertelanjang dada di depan Ben.
Ada semacam sensasi bahaya yang mengendap-endap di dalam Burning. Dan kita tak tahu pasti apa itu. Saya lebih suka untuk berpikir bahwa apa yang terjadi tak seperti kelihatannya. Karena pilihan tersebut memang lebih nyaman. Namun, tetap ada rasa yang mengganjal bahwa apa yang terjadi memang seperti yang kita kira. Lebih mengerikan untuk dibayangkan, tapi tak apa, karena Jongsu sudah mendapat sebuah pelepasan. Kotak radioaktif kucing Schrodinger diputuskan untuk dimusnahkan. ■UP
Follow Ulasan Pilem di twitter: @ulasanpilem dan di instagram: @ulasanpilem
Kunjungi Ulasan Pilem di facebook: facebook.com/ulasanpilem


Burning
148 menit
Dewasa
Lee Chang-dong
Oh Jung-mi, Lee Chang-dong (screenplay), Haruki Murakami (cerita)
Lee Joon-dong, Lee Chang-dong
Hong Kyung-pyo
Mowg
'Burning' adalah pencapaian hebat dalam hal penciptaan suspens.

“Why do we live? What is the significance of living?”Rating UP:
— Shin Hae-mi
Sepanjang sejarah perfilman thriller, Burning barangkali merupakan salah satu film yang paling tak konklusif dari segi misteri. Namun, secara emosional, ia sangat memuaskan. Film ini dibangun dengan perlahan tapi sangat terukur, mencekat kita lewat cara yang tak terduga sembari memberi cukup ruang agar bobot emosionalnya terakumulasi dengan begitu hebat. Semua ini kemudian mengantarkan kita ke momen puncak yang saking gregetnya kita merasa sangat butuh sebuah pelepasan. Tidak bisa tidak. Wajib.
"Ya Tuhan, satu pelepasan saja dan saya akan lega," kita pikir.
Dan BAM! Burning memberikannya dengan cara dan waktu yang tepat.
Saya bisa menggambarkan Burning dengan deskripsi sederhana: sebuah cinta segitiga yang berujung pada cerita kriminal. Tapi saya bakal sotoy. Film ini jauh lebih kompleks daripada itu. Lagipula, saya tak tahu apakah deskripsi tersebut memang mewakili atau tidak. Saya bisa saja menonton film ini lebih dari 10 kali, dan ujung-ujungnya tetap saja tak bakal sepenuhnya yakin dengan apa yang (saya kira) saya lihat. Burning penuh dengan ketidakpastian dan justru itulah yang membuatnya sangat menegangkan.
Kita sebagai penonton, sama seperti para karakter di dalam film, tak persis tahu apa yang sebenarnya terjadi dan melihat karakter lain lewat kacamata masing-masing; persepsi yang sebetulnya hanyalah produk ambigu dari pengalaman hidup yang cuma sebentar dengan orang yang dimaksud. Apakah mereka memang betul seperti apa yang kita kira?
Mari kita mulai dengan karakter utama kita, Jongsu (Yoo Ah-in), pria kampung yang bercita-cita menjadi penulis walau saat ini hanya berkutat sebagai kurir di kota Seoul. Jongsu pendiam dan tak begitu ekspresif. Ia hanyalah pria biasa yang sama sekali tak mencolok. Namun seorang SPG seksi yang ditemuinya tak sengaja di jalan bilang bahwa mereka saling kenal. Katanya mereka dulu adalah teman sekelas di kampung. Jongsu melongo.
"Aku operasi plastik," celoteh si SPG. Cewek ini namanya Haemi (Jeon Jong-seo), seorang optimis, penuh semangat, dan tampaknya sangat polos. Saat nongkrong, Haemi kemudian bilang kepada Jongsu bahwa ia sedang mempelajari pantomim. Tak butuh lama, Jongsu diajak main ke apartemen Haemi dan mereka melakukan hal yang iya-iya disana.
Jelas sekali kalau Jongsu langsung merasa terikat dengan Haemi. Ia bahkan mau saja saat dimintai tolong untuk memberi makan kucing Haemi selama Haemi pergi ke Afrika dalam sebuah perjalanan mencari jati diri. Setiap hari Jongsu mengunjungi apartemen Haemi, dan setiap hari itu pula ia merancap sambil membayangkan Haemi.
Iya. Merancap. Jongsu memang punya kehidupan yang sedikit, ehm, ganjil. Ia seperti selalu sendirian dan tak punya satu pun teman. Kita mendengar bahwa ayahnya sedang dalam masalah, tapi kita tak perlu tahu persisnya apa. Kita tahu bahwa sang ibu sudah meninggalkannya. Kita tahu Jongsu rutin mengunjungi kebun ayahnya di kampung. Film menuturkan detail kehidupan Jongsu dengan perlahan dan telaten, tapi rasa-rasanya gambaran besarnya masih saja buram.
Namun yang lebih buram adalah Ben (Steven Yeun). Jongsu ketemu Ben saat menjemput Haemi di bandara sekembalinya dari Afrika. Situasi ini menciptakan hubungan segitiga yang tak nyaman. Ben adalah teman seperjalanan Haemi. Tapi mereka sepertinya sangat akrab. Apakah mereka jadian? Entahlah. Haemi sepertinya menikmati sekali saat jalan dengan Ben, tapi ia juga berusaha untuk selalu mengajak Jongsu. Ben tampaknya juga tak pernah keberatan.
Jongsu punya firasat buruk soal Ben. Ada sesuatu yang janggal dengan Ben; ia sosialita, punya mobil Porsche dan apartemen mewah, tapi kelihatannya tak punya pekerjaan. Kepribadiannya mulus tapi nyaris hampa, bahkan mungkin punya bakat psikopat. Ben memberitahu Jongsu dan Haemi bahwa ia tak pernah menangis seumur hidup. Penampilan Steven Yeun luar biasa; ia menciptakan karakter dingin yang penuh misteri.
Film ini memang punya kemasan thriller kriminal. Namun ia lebih terasa seperti studi psikologi karakter. Atau barangkali lebih tepat: permainan studi psikologi karakter. Kita melihat sesuatu cukup banyak, tapi kita tetap saja tak tahu banyak. Apa maksud Ben terhadap Jongsu? Atau terhadap Haemi?
Atau soal Haemi sendiri. Apakah ia benar bisa dipercaya? Apakah Jongsu dulu memang pernah menyelamatkan Haemi saat terjebak di sumur? Atau itu hanya karangan Haemi belaka? Cerita film ini seolah cerita antara dua orang pria yang sangat berbeda dengan satu wanita polos terjebak di tengahnya. Apa benar begitu? Kebenaran hakiki adalah sebuah kemustahilan dalam Burning. Kita diperdaya untuk membuat asumsi yang belum tentu kebenarannya.
Ketika Haemi tiba-tiba menghilang, Jongsu hampir sepenuhnya yakin bahwa pelakunya adalah Ben, walau tak ada bukti yang jelas. Ini memancing Jongsu untuk membuntuti Ben. Jongsu ingat bahwa Ben pernah bilang bahwa ia suka membakar greenhouse; bukan untuk apa-apa, melainkan hanya untuk sekadar melihat greenhouse tersebut terbakar. Dan target selanjutnya, kata Ben sembari tersenyum, berada sangat dekat dengan Jongsu. Jongsu sangat percaya dengan ini sampai ia mengecek semua greenhouse di kampungnya. Jongsu tak menemukan apapun. Apakah Ben benar-benar tukang bakar atau cuma sedang mempermainkannya?
Film ini digarap oleh sutradara Lee Chang-dong dari cerita pendek karya penulis kenamaan Jepang, Haruki Murakami. Plotnya terasa berjalan dengan alami meski latarnya diubah menjadi di Korea. Film Lee dengan luar biasa menangkap nuansa kesendirian dan hasrat terpendam yang kerap ditemui dalam karya Murakami. Poin utamanya adalah apa yang diutarakan Haemi kepada Jongsu sebelum berangkat ke Afrika: "Semua orang lapar akan sesuatu."
Burning adalah pencapaian hebat dalam hal penciptaan suspens. Kita sukses dijaga untuk merasa tak nyaman dalam durasinya yang sangat panjang, nyaris 3 jam. Metode narasinya barangkali adalah aplikasi sinematis dari teori Kucing Schrodinger. Teori ini menyebutkan bahwa seekor kucing yang dimasukkan ke dalam kotak radioaktif, berada dalam kondisi hidup dan mati secara simultan. Kita belum tahu status kucingnya almarhum atau bukan sebelum kita melihat isi kotak tersebut. Entah sengaja atau tidak, Lee bahkan menyelipkan Kucing Schrodinger ala-ala ke dalam Burning. Jongsu dengan rutin memberi makan kucing Haemi, tapi ia tak pernah melihat wujud kucing tersebut. Meski begitu, makanannya selalu habis.
Saya sengaja bawa-bawa teori fisika kuantum biar dibilang intelek.
Lee tidak menciptakan Kucing Schrodinger-nya dengan manipulasi palsu. Alih-alih, ia melakukannya dengan memberikan latar situasi yang sedemikian kompleks demi menciptakan tensi. Ada perbedaan strata sosial dan kepribadian yang mencolok antara Jongsu dengan Ben. Apakah Jongsu merasa iri terhadap Ben? Ataukah Jongsu murka karena Ben tak mengapresiasi Haemi seperti ia menyukai Haemi? Saat Haemi bercerita di depan teman-teman Ben, Jongsu melihat sekilas Ben yang menguap bosan. Dan barangkali tak tahu itu semua, Haemi malah dengan nyaman menari bertelanjang dada di depan Ben.
Ada semacam sensasi bahaya yang mengendap-endap di dalam Burning. Dan kita tak tahu pasti apa itu. Saya lebih suka untuk berpikir bahwa apa yang terjadi tak seperti kelihatannya. Karena pilihan tersebut memang lebih nyaman. Namun, tetap ada rasa yang mengganjal bahwa apa yang terjadi memang seperti yang kita kira. Lebih mengerikan untuk dibayangkan, tapi tak apa, karena Jongsu sudah mendapat sebuah pelepasan. Kotak radioaktif kucing Schrodinger diputuskan untuk dimusnahkan. ■UP
Follow Ulasan Pilem di twitter: @ulasanpilem dan di instagram: @ulasanpilem
Kunjungi Ulasan Pilem di facebook: facebook.com/ulasanpilem