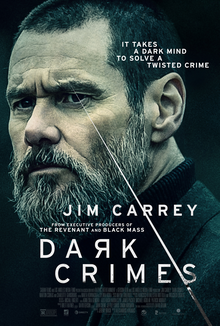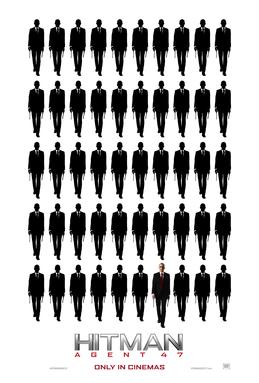Judul : Review Film: 'Sicario 2: Day of the Soldado' (2018)
link : Review Film: 'Sicario 2: Day of the Soldado' (2018)
Kriminal
Taylor Sheridan sepertinya mampu bikin cerita apa saja menjadi menarik dan menegangkan.

“You got to do what you got to do.”Rating UP:
— Alejandro
Taylor Sheridan (Hell or High Water, Wind River) sepertinya mampu bikin cerita apa saja menjadi menarik dan menegangkan. Ia bahkan mungkin bisa membuat riwayat asmara saya yang biasa-biasa saja menjadi film aksi-thriller brutal yang mencekam... dengan banyak nyawa melayang di dalamnya.
Itu adalah testimoni saya mengenai keterampilan skrip Sheridan dalam Sicario 2: Day of the Soldado. Bahkan saat disini ia harus kehilangan empat pemain kunci dari film pertama: aktris Emily Blunt, sutradara Denis Villeneuve, sinematografer Roger Deakins, dan komposer Johann Johannsson. Bahkan saat ia relatif tak punya cerita untuk diceritakan. Yang dibutuhkannya cuma beberapa kru yang lumayan, sutradara yang cukup berkomitmen, dan pemain utama yang karismatik.
Soldado jelas tak sengehek Sicario. Selain karena aspek teknisnya yang sedikit lebih superior, sebagian besar penyebabnya adalah karena ia tak punya hooking point yang dimiliki oleh film pertama, yang dihadirkan lewat kenaifan karakter Blunt yang menyaksikan betapa abu-abunya batas moralitas dalam lingkaran konflik perdagangan narkoba. Kita dibuat syok dengan pengungkapan bahwa penegak keadilan tak jauh berbeda korup dan kejinya dengan para kriminal yang mereka berantas. Soldado hanya sedikit menyampaikan hal baru mengenai sistem pemerintahan yang kebablasan ini, namun ia mampu berdiri dengan kokoh sebagai film aksi-drama yang cukup mengikat.
Setelah menonton Sicario, kita sudah tahu bahwa hanya akan ada sedikit sensitivitas moral yang dipunyai oleh karakter kuncinya. Absennya karakter Blunt membuat perspektif dalam Soldado bergeser. Agen lapangan CIA, Matt Graver (Josh Brolin) dan pembunuh bayaran, Alejandro (Benicio Del Toro) yang sebelumnya menjadi karakter sampingan, sekarang adalah karakter utama. Kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang berseragam yang tak punya aturan. Sedari awal, Matt tak ragu-ragu menerapkan metode yang jauh lebih kejam daripada waterboarding saat menginterogasi seorang bajak laut Somalia.
Karisma Brolin dan Del Toro begitu kuat hingga mereka menguasai momen apapun saat muncul di layar. Gaya slenge'an karakter Matt yang pernah ke markas dengan sendal jepit tak lagi akan anda ingat, sebab Brolin kali ini lebih serius. Misi adalah prioritasnya, tapi ada sedikit nuansa pemberontakan yang terasa di dalam dedikasinya. Sementara Del Toro... aktor ini mampu berbuat banyak tanpa perlu banyak bacot. Ia hanya perlu berdiri lalu menatap tajam, dan kita akan bergidik. Ia adalah pembunuh yang efektif, dan meski saya sama sekali tak mendukung ini, ia sukses membuat aksi membantai orang terlihat keren.
Soldado dimulai dengan segerombolan imigran ilegal yang melintasi perbatasan Meksiko-Amerika di tengah malam buta. Mereka bukan imigran biasa, karena saat hampir terciduk, mereka meledakkan diri. Di lain waktu, bom bunuh diri juga terjadi di sebuah supermarket di Amerika. Teroris kah? Bagaimana mereka bisa masuk ke Amerika? Salah satu alasannya adalah karena tembok raksasa nan mutakhir buatan presiden Trump belum jadi. Namun karena ini bukan film politik, maka yang menjadi biang keroknya ternyata adalah kartel narkoba. Katanya, menyusupkan manusia jauh lebih menguntungkan daripada menyelundupkan kokain.
Pemerintah, lewat karakter yang diperankan Matthew Modine dan Catherine Keener, kemudian menghubungi seseorang yang patut dihubungi saat mereka harus melakukan pekerjaan kotor: Matt Graver. Misi Matt adalah menculik Isabel Reyes (Isabela Moner), anak gadis dari seorang bos kartel, lalu membuatnya terkesan sebagai aksi dari kartel sebelah. Dengan begini, mereka akan saling menyalahkan, dan otomatis akan saling bantai lewat perang antarkartel. Pemerintah Amerika bisa ongkang-ongkang kaki. Rencananya sih begitu.
Untuk melakukan ini, Matt merekrut kenalan lamanya, Alejandro yang juga punya dendam lama kepada sang bos kartel. Kebetulan. Tentu saja, semua tak berjalan dengan lancar. Terlebih saat sebagian besar polisi Meksiko ternyata digaji oleh kartel. Saat situasi menjadi kacau, pemerintah Amerika bermaksud cuci tangan. Tapi tim Matt dan Alejandro sudah terlanjur basah. Ya sudah, mandi sekalian.
Sementara itu, dalam bagian yang tak begitu menarik, kita diperkenalkan dengan Miguel (Elijah Rodriguez), remaja Amerika berdarah Meksiko yang tinggal di perbatasan. Ia direkrut oleh kartel sebagai salah satu eksekutor penyelundupan manusia. Tentu saja, nanti petualangan Miguel akan bersilangan dengan karakter utama kita. Saya rasa, momen ini dimaksudkan untuk memberi dampak emosional yang lumayan tajam. Meski begitu, perjalanan karakter yang klise dengan karakterisasi yang kurang mengesankan, membuatnya terasa hambar. Subplot mengenai Miguel terasa sedikit mendistraksi, padahal ini berperan penting nantinya.
Namun ini adalah komplain kecil kalau dibandingkan dengan bagaimana terampilnya Sheridan membangun cerita dan mengatur ritme. Menjelang akhir, ada momen krusial yang sebenarnya terkesan mustahil terjadi dalam konteks film "serius". Tapi nyatanya lumayan bekerja, karena kita sebelumnya dikondisikan untuk berharap itu bakal bekerja, setidaknya selama kita menonton. Saya mencoba sotoy nih, tapi saya yakin sutradara Stefano Sollima lumayan setia mengikuti visi Sheridan. Soalnya, Soldado tetap terasa berlangsung di semesta yang sama dengan Sicario, meski atmosfernya memang tak semisterius itu. Mayoritas intensitas tak lagi tercipta berkat atmosfer, melainkan penanganan sekuens aksi yang kompeten oleh Sollima. Adegan penyergapan di jalanan gurun Meksiko berisi cukup suspens hingga kita terhenyak saat huru-hara yang sesungguhnya dilepaskan.
Kalau dibandingkan dengan Sicario, film ini memang lebih dangkal. Jika yang ingin disampaikan Sheridan adalah soal ambiguitas moral, maka ia sudah membeberkan semuanya lewat film pertama. Bahkan usaha untuk memanusiakan karakter Alejandro juga terasa biasa sekali; ia sekarang (agaknya) menjadi tokoh antihero yang konvensional. Sebetulnya, sulit membayangkan bagaimana film semacam Sicario bisa menghasilkan sekuel. Namun Sheridan pandai mengemas barang receh. Disini, ia bahkan ia mampu menge-set kemungkinan baru yang menjanjikan sesuatu lebih besar yang akan datang. ■UP
Follow Ulasan Pilem di twitter: @ulasanpilem dan di instagram: @ulasanpilem
Kunjungi Ulasan Pilem di facebook: facebook.com/ulasanpilem


Sicario: Day of the Soldado
122 menit
Dewasa
Stefano Sollima
Taylor Sheridan
Basil Iwanyk, Edward L. McDonnell, Molly Smith, Thad Luckinbill, Trent Luckinbill
Dariusz Wolski
Hildur Guðnadóttir
Taylor Sheridan sepertinya mampu bikin cerita apa saja menjadi menarik dan menegangkan.

“You got to do what you got to do.”Rating UP:
— Alejandro
Taylor Sheridan (Hell or High Water, Wind River) sepertinya mampu bikin cerita apa saja menjadi menarik dan menegangkan. Ia bahkan mungkin bisa membuat riwayat asmara saya yang biasa-biasa saja menjadi film aksi-thriller brutal yang mencekam... dengan banyak nyawa melayang di dalamnya.
Itu adalah testimoni saya mengenai keterampilan skrip Sheridan dalam Sicario 2: Day of the Soldado. Bahkan saat disini ia harus kehilangan empat pemain kunci dari film pertama: aktris Emily Blunt, sutradara Denis Villeneuve, sinematografer Roger Deakins, dan komposer Johann Johannsson. Bahkan saat ia relatif tak punya cerita untuk diceritakan. Yang dibutuhkannya cuma beberapa kru yang lumayan, sutradara yang cukup berkomitmen, dan pemain utama yang karismatik.
Soldado jelas tak sengehek Sicario. Selain karena aspek teknisnya yang sedikit lebih superior, sebagian besar penyebabnya adalah karena ia tak punya hooking point yang dimiliki oleh film pertama, yang dihadirkan lewat kenaifan karakter Blunt yang menyaksikan betapa abu-abunya batas moralitas dalam lingkaran konflik perdagangan narkoba. Kita dibuat syok dengan pengungkapan bahwa penegak keadilan tak jauh berbeda korup dan kejinya dengan para kriminal yang mereka berantas. Soldado hanya sedikit menyampaikan hal baru mengenai sistem pemerintahan yang kebablasan ini, namun ia mampu berdiri dengan kokoh sebagai film aksi-drama yang cukup mengikat.
Setelah menonton Sicario, kita sudah tahu bahwa hanya akan ada sedikit sensitivitas moral yang dipunyai oleh karakter kuncinya. Absennya karakter Blunt membuat perspektif dalam Soldado bergeser. Agen lapangan CIA, Matt Graver (Josh Brolin) dan pembunuh bayaran, Alejandro (Benicio Del Toro) yang sebelumnya menjadi karakter sampingan, sekarang adalah karakter utama. Kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang berseragam yang tak punya aturan. Sedari awal, Matt tak ragu-ragu menerapkan metode yang jauh lebih kejam daripada waterboarding saat menginterogasi seorang bajak laut Somalia.
Karisma Brolin dan Del Toro begitu kuat hingga mereka menguasai momen apapun saat muncul di layar. Gaya slenge'an karakter Matt yang pernah ke markas dengan sendal jepit tak lagi akan anda ingat, sebab Brolin kali ini lebih serius. Misi adalah prioritasnya, tapi ada sedikit nuansa pemberontakan yang terasa di dalam dedikasinya. Sementara Del Toro... aktor ini mampu berbuat banyak tanpa perlu banyak bacot. Ia hanya perlu berdiri lalu menatap tajam, dan kita akan bergidik. Ia adalah pembunuh yang efektif, dan meski saya sama sekali tak mendukung ini, ia sukses membuat aksi membantai orang terlihat keren.
Soldado dimulai dengan segerombolan imigran ilegal yang melintasi perbatasan Meksiko-Amerika di tengah malam buta. Mereka bukan imigran biasa, karena saat hampir terciduk, mereka meledakkan diri. Di lain waktu, bom bunuh diri juga terjadi di sebuah supermarket di Amerika. Teroris kah? Bagaimana mereka bisa masuk ke Amerika? Salah satu alasannya adalah karena tembok raksasa nan mutakhir buatan presiden Trump belum jadi. Namun karena ini bukan film politik, maka yang menjadi biang keroknya ternyata adalah kartel narkoba. Katanya, menyusupkan manusia jauh lebih menguntungkan daripada menyelundupkan kokain.
Pemerintah, lewat karakter yang diperankan Matthew Modine dan Catherine Keener, kemudian menghubungi seseorang yang patut dihubungi saat mereka harus melakukan pekerjaan kotor: Matt Graver. Misi Matt adalah menculik Isabel Reyes (Isabela Moner), anak gadis dari seorang bos kartel, lalu membuatnya terkesan sebagai aksi dari kartel sebelah. Dengan begini, mereka akan saling menyalahkan, dan otomatis akan saling bantai lewat perang antarkartel. Pemerintah Amerika bisa ongkang-ongkang kaki. Rencananya sih begitu.
Untuk melakukan ini, Matt merekrut kenalan lamanya, Alejandro yang juga punya dendam lama kepada sang bos kartel. Kebetulan. Tentu saja, semua tak berjalan dengan lancar. Terlebih saat sebagian besar polisi Meksiko ternyata digaji oleh kartel. Saat situasi menjadi kacau, pemerintah Amerika bermaksud cuci tangan. Tapi tim Matt dan Alejandro sudah terlanjur basah. Ya sudah, mandi sekalian.
Sementara itu, dalam bagian yang tak begitu menarik, kita diperkenalkan dengan Miguel (Elijah Rodriguez), remaja Amerika berdarah Meksiko yang tinggal di perbatasan. Ia direkrut oleh kartel sebagai salah satu eksekutor penyelundupan manusia. Tentu saja, nanti petualangan Miguel akan bersilangan dengan karakter utama kita. Saya rasa, momen ini dimaksudkan untuk memberi dampak emosional yang lumayan tajam. Meski begitu, perjalanan karakter yang klise dengan karakterisasi yang kurang mengesankan, membuatnya terasa hambar. Subplot mengenai Miguel terasa sedikit mendistraksi, padahal ini berperan penting nantinya.
Namun ini adalah komplain kecil kalau dibandingkan dengan bagaimana terampilnya Sheridan membangun cerita dan mengatur ritme. Menjelang akhir, ada momen krusial yang sebenarnya terkesan mustahil terjadi dalam konteks film "serius". Tapi nyatanya lumayan bekerja, karena kita sebelumnya dikondisikan untuk berharap itu bakal bekerja, setidaknya selama kita menonton. Saya mencoba sotoy nih, tapi saya yakin sutradara Stefano Sollima lumayan setia mengikuti visi Sheridan. Soalnya, Soldado tetap terasa berlangsung di semesta yang sama dengan Sicario, meski atmosfernya memang tak semisterius itu. Mayoritas intensitas tak lagi tercipta berkat atmosfer, melainkan penanganan sekuens aksi yang kompeten oleh Sollima. Adegan penyergapan di jalanan gurun Meksiko berisi cukup suspens hingga kita terhenyak saat huru-hara yang sesungguhnya dilepaskan.
Kalau dibandingkan dengan Sicario, film ini memang lebih dangkal. Jika yang ingin disampaikan Sheridan adalah soal ambiguitas moral, maka ia sudah membeberkan semuanya lewat film pertama. Bahkan usaha untuk memanusiakan karakter Alejandro juga terasa biasa sekali; ia sekarang (agaknya) menjadi tokoh antihero yang konvensional. Sebetulnya, sulit membayangkan bagaimana film semacam Sicario bisa menghasilkan sekuel. Namun Sheridan pandai mengemas barang receh. Disini, ia bahkan ia mampu menge-set kemungkinan baru yang menjanjikan sesuatu lebih besar yang akan datang. ■UP
Follow Ulasan Pilem di twitter: @ulasanpilem dan di instagram: @ulasanpilem
Kunjungi Ulasan Pilem di facebook: facebook.com/ulasanpilem